Memikirkan Ulang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang Demokratis
- M. Roby Septiyan

- 1 Jul 2022
- 3 menit membaca
Teman-teman angkatan 2020–tentu juga saya–tentunya masih ingat dengan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah. Dalam mata kuliah tersebut–tepatnya pada materi kebijakan bahasa–kita diajarkan bahwa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional karena sifatnya yang demokratis. Bukti dari kedemokratisan bahasa Indonesia antara lain tidak membeda-bedakan sebutan bagi lawan bicara. Pada mulanya hal tersebut saya terima, mungkin teman-teman pun sama halnya. Penerimaan itu tidak lebih karena saya adalah mahasiswa yang tolol menurut sebagian orang. Saya pasif di dalam kelas, jarang sekali bertanya, dan hanya berbicara pada beberapa kesempatan yang memang mengharuskan saya untuk bicara.
Pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang demokratis terus menguat sebagai suatu kebenaran, sampai saya mencoba kembali pada sebelum adanya bahasa Indonesia. Tentunya saya tidak bisa menjelajah ke waktu terdahulu, maka usaha saya adalah menilik kembali bahasa daerah di Indonesia. Saya kembali ke bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Pada mulanya bahasa Indonesia tetap demokratis, sedangkan bahasa Sunda tidak demokratis. Hal itu diperparah dengan pengetahuan saya mengenai undak usuk yang membeda-bedakan pilihan kata, nada suara, dan perilaku sesuai dengan lawan bicara.
Undak usuk dalam bahasa Sunda ternyata memang menjadi masalah bagi orang Sunda di alam demokrasi. Hal ini termuat dalam buku Polémik Undak Usuk Basa Sunda (1987) yang dimulai oleh Ajip Rosidi, biarpun wacana mengenai pendemokrasian bahasa Sunda sudah ada jauh sebelum tahun itu. Apa kaitan buku ini dengan bahasa Indonesia yang demokratis? Dalam buku tersebut Saini KM menyatakan bahwa pada revolusi-revolusi ke arah era nasionalis di Eropa, golongan borjuis yang rata-rata berprofesi sebagai saudagarlah yang memenangkan keuntungan paling banyak. Segala sesuatu menjadi harus sesuai dengan kebiasaan kaum saudagar yang sifatnya efektif dan efisien atau lugas dan logis. Bahasa pun harus seperti itu, maka dipilihlah bahasa yang tidak mementingkan perasaan, suasana, situasi, asosiasi-asosiasi, status penutur dan mitra tutur [1]. Bahasa yang dipilih tersebut maka akan direkayasa sedemikian mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan penguasa.
Pernyataan Saini KM membuat saya berpikir mungkin juga bila bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional karena sifatnya yang efektif dan efisien, setidaknya sangat berpotensi untuk dijadikan efektif dan efisien dan bukan karena kedemokratisannya. Pikiran ini didukung oleh wacana yang populer tentang bahasa Melayu–cikal bakal bahasa Indonesia–yang digunakan sebagai bahasa perdagangan di Nusantara. Selain itu, upaya rekayasa bahasa ke arah efektif dan efisien juga terlihat dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah–setidaknya yang saya alami–yang di antara muatan ajarnya adalah menjadikan suatu kalimat menjadi efektif dan efisien dengan berbagai cara.
Saini KM dalam sumber yang sama juga menyatakan secara tidak langsung bahwa tidak ada bahasa yang demokratis. Beberapa contoh dilampirkannya, misalnya dalam bahasa Inggris, wanita yang baik tingkah lakunya disebut like a lady atau ladylike; orang yang sopan santun disebut corteous (seperti orang keraton) dll. Saya mencoba memasukan contoh-contoh itu ke dalam bahasa Indonesia, bertemulah saya dengan perumpamaan-perumpamaan semacam kata putri sebagai sebutan bagi anak perempuan yang cantik dan anggun. Pikiran saya secara spontan menerima hal tersebut, tidak mungkin anak perempuan yang cantik dan anggun diumpamakan sebagai tukang becak. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam bahasa tetap mengendap budaya-budaya para pendahulu, apalagi jika endapan itu sesuai kebutuhan penguasa. Kemudian endapan itu akan menjadi hal yang dipaksakan untuk meresap pada generasi berikutnya yang belum lahir, sama seperti nilai-nilai sosial lain di masyarakat.
Sedari awal tulisan ini, saya sering kali menggunakan kata “mungkin”. Tentunya menunjukan keragu-raguan dan memang begitu. Keraguan saya didasari pada pertemuan dengan kenyataan dalam praktis berbahasa dalam keseharian. Bahasa yang efektif dan efisien tetap digunakan karena dalam beberapa keadaan yang menggunakan bahasa yang tidak efektif dan efisien menyebabkan kesalahpahaman.
Apakah bahasa Indonesia benar-benar demokratis? Lebih dari itu, pernyataan-pernyataan sebelumnya membuat kita sadar bahwa dalam berbahasa ada banyak kemungkinan kita ini dikontrol dan dikuasai oleh golongan lain. Lebih buruk dari itu adalah kenyataan bahwa mungkin saja kita menggunakan bahasa untuk mengontrol dan menguasai orang lain dengan tujuan yang salah.
Saya–melalui tulisan, media yang nyaman bagi saya–mengajak teman-teman untuk memikirkan ulang bahasa Indonesia sebagai bahasa yang demokratis.
Cag!
[1] Saini KM, “Undak Usuk Dina Basa Sunda: Catetan kana Sabagian Makalah Ajip Rosidi” dalam Polemik Undak Usuk Basa Sunda (PT Mangle Panglipur, 1987), hal 29–33




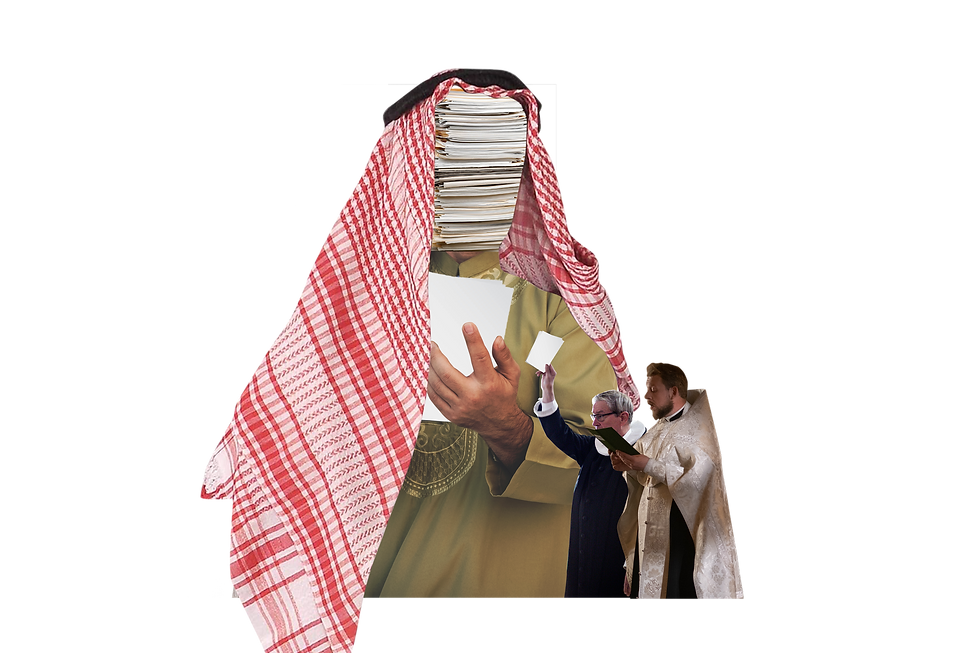
Komentar